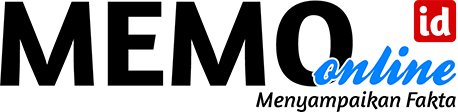Foto: Penulis Latif Fianto
Foto: Penulis Latif Fianto
Sebuah Perlawanan dalam Laut Bercerita
 Foto: Penulis Latif Fianto
Foto: Penulis Latif Fianto
Oleh: Latif Fianto
MEMOonline.co.id - “Jangan sedih. Ibumu pasti sedang mengalami yang kualami. Dan kamu harus mengatakan bahwa kau membutuhkannya. Dia bukan melupakanmu. Dia menanggung luka yang tak tersembuhkan karena ketidaktahuan jauh lebih keji. Kita tak bisa berdoa ke makam anak kita.”
Kutipan di atas saya ambil dari novel Laut Bercerita karangan Leila S. Chudori. Itu hanya sepenggal paragraf dari banyak penggalan paragraf lain yang menyeret saya masuk ke dalam kesedihan. Ke kedalaman laut yang sunyi. Yang mau tak mau menyeret saya pada perasaan milankolis yang membuncahkan air mata.
Apakah saya termasuk lelaki cengeng? Kalau kau mengambil kesimpulan demikian, tak apa. Tapi saya percaya, kau pasti memiliki satu titik di mana kau tidak mampu menahan air mata saat memperhatikan satu pemandangan perih di depan pucuk hidung. Apakah pemandangan itu seorang lelaki tua berusia senja yang tertatih-tatih memikul kayu untuk ditukar dengan uang; apakah seorang anak kecil yang mengemis dari pintu kafe ke pintu kafe; atau seorang pedagang kaki lima yang mengharap kedatangan pembeli di ujung senja yang sekarat.
Untuk yang satu ini saya pernah bertanya kepada seorang teman: kenapa saya begitu tersentuh dan selalu menangis saat membaca kisah atau menonton film yang terlanjur sedih maupun yang terlampau haru? Kalau tidak keliru ia menjawab begini. Itulah kenapa namamu Latif. Hatimu terlalu lembut dan mudah tersentuh.
Saya mengamini perkataannya. Mungkin benar. Sebuah nama adalah sebuah representasi dari diri dan jiwa seseorang.
Saya tertarik membeli novel Laut Bercerita ketika seorang teman mem-posting-nya di instagram. Sebenarnya, jauh sebelum itu saya sudah mengetahuinya. Tapi ketika ia menaruhnya di instagram, saya semakin tertarik dan mencari informasi tentang novel itu. Karena harganya cukup mahal untuk ukuran kantong saya yang kerap kering, keinginan untuk membelinya lambat laun semakin memudar. Hingga dalam perjalanan waktu, saya malah tertarik membawa pulang The Red-Haired Woman karangan si peraih Nobel Sastra, Orhan Pamuk, dari Togamas dan Vegetariannya Han Kang dan Don’t Let Me Go karangan Kazuo Ishiguro, si peraih Nobel Sastra tahun 2017, dari Gramedia.
Namun pada suatu hari, ketika tersebar panflet pemutaran film dan diskusi novel Laut Bercerita di Fakultas Hukum UB, saya berusaha hadir mendengarkan penjelasan langsung Leila S. Chudori tentang bagaimana novel itu ditulis, bersama narasumber lain seperti dari pihak produksi film pendek Laut Bercerita, keluarga salah satu korban penghilangan paksa tragedi 1998, Suciwati istri Munir, perwakilan dari Amnesty International Indonesia, dan perwakilan dari pihak Fakultas Hukum UB.
Dari yang awalnya tidak tertarik membeli novel tersebut, tetapi demi ingin berfoto dan memperoleh tanda tangan penulisnya, saya yang saat itu sudah turun sehabis berfoto dengan Suciwati, naik lagi ke lantai 6 untuk membeli novel Laut Bercerita dan merangsek maju ke hadapan Leila. Akhirnya saya memiliki salah satu novel Leila, dibubuhi tanda tangan penulisnya, dan berfoto dengannya. Saya pernah membolak-balik novel Leila sebelumnya, Pulang, di rak buku Togamas. Tapi saat itu saya tidak tertarik membawanya pulang ke kos karena pertimbangan finansial. Terlebih lagi, saya jarang membawa novel-novel dalam negeri karena pertimbangan-pertimbangan tertentu.
Kau mungkin akan mengerti di sudut mana saya berada. Jujur, selain karena faktor finansial, saya termasuk yang begitu lambat mengikuti perkembangan sastra Indonesia dan dunia dan termasuk salah seorang yang begitu lambat dalam membaca. Kau bayangkan sendiri, saya tidak tahu tepatnya, mungkin saat saya duduk di semester dua, saya membeli buku Dialektika Marxis (Sejarah Kesadaran Kelas) karangan Georg Lukacs. Kalau tidak keliru saya baru membacanya dua lembar dan setelah itu saya tinggalkan di rak buku. Kenapa? Karena saya tidak mengerti apa yang sebenarnya dibahas di situ. Dan sampai saat ini, saya belum berhasil membukanya kembali.
Saat duduk di semester lima, itu kalau saya tidak keliru mengingat, saya membeli buku lagi: Dunia yang Dilipat karangan Yasraf Amir Piliang. Saya sedikit bisa memasuki buku ini pelan-pelan. Kau bisa bilang, selama kuliah, saya hanya berhasil membeli dua buku. Itu pun saya tidak berhasil menuntaskan dua-duanya—ini jelas perilaku mahasiswa yang tidak patut dicontoh. Saya berpikir, masih terlalu banyak buku yang belum saya baca. Dan saya memilih untuk membeli dan membaca buku-buku primer yang prioritas. Itulah kenapa saya tidak terlalu tahu perkembangan sastra dalam negeri. Bahkan jika dibanding temanku yang kuliah di Universitas Kanjuruhan, Suri namanya, saya adalah manusia dengan pengetahuan yang sangat minim. Itu kalau tabungan pengetahuan diukur dari banyaknya jumlah buku yang ada di kamar.
Itulah kenapa ketika saya mau membeli novel karangan Leila S. Chudori, saya harus mempertimbangkan banyak hal. Salah satunya: apakah buku-buku karangan novelis yang juga jurnalis itu patut dibaca dalam waktu sesegera mungkin. Meski saya tahu, novel pertamanya yang berjudul Pulang memenangkan Prosa Terbaik Khatulistiwa Literary Award 2013 dan dinyatakan sebagai satu dari “75 Notable Translations of 2016” oleh World Literature Today. Catatan keberhasilan novel Leila ini saya kutip dari profil Leila dalam novel Laut Bercerita.
Boleh dikata, saya termasuk manusia yang selektif. Bahkan ketika saya mendengarkan langsung beberapa testimoni mahasiswa dan dosen yang sudah pernah membaca novel karangan Leila, termasuk setelah saya mendengar langsung pemaparan Leila mengenai novel yang sudah ditulisnya itu, saya masih belum tergerak membeli novel tersebut. Kalaupun pada akhirnya saya membelinya, itu hanya karena saya merasa tidak sopan mau berfoto bersamanya tanpa menenteng satu pun buku karangannya.
Ketika mulai membaca prolog novel Laut Bercerita, saya menangkap indikasi bahwa novel itu sangat luar biasa. Tetapi saya memilih menyimpannya terlebih dahulu di rak buku. Ada tiga novel yang saya selesaikan dalam kurang lebih tiga minggu sebelum akhirnya saya membaca kembali Laut Bercerita dan menuntaskannya. Pada beberapa bagian, saya terpaksa harus menahan tetes air mata. Terutama ketika si penutur berganti Asmara Jati, adik Biru Laut. Ada kesedihan yang mencekam di sana. Ada ikatan cinta yang tulus. Ada kebanggaan sekaligus usaha yang tidak sia-sia di dalamnya. Dan saya harus mengatakan, Leila berhasil mengaduk-aduk emosi saya. Laut Bercerita benar-benar membuka kembali cerita kelam perlawanan anak-anak muda, yang darahnya begitu hangat dan bergelora, yang memiliki idealisme dan keyakinan tinggi, untuk keluar dari kungkungan rezim represif Orde Baru. Leila sungguh berhasil meramu kisah itu dengan kata-kata yang kadar rasanya di masing-masing sisi pas dan tidak berlebihan.
Membaca Laut Bercerita adalah pengalaman luar biasa. Saya bisa membayangkan aktivitas mahasiswa saat itu dengan kegiatan mahasiswa (termasuk saya) dewasa ini, terutama mereka yang tinggal di lingkungan saya tinggal sekarang. Mereka, Biru Laut dan kawan-kawannya, membaca karya-karya Pramoedya Ananta Toer, yang saat itu dilarang terbit dan dibaca, dan mendiskusikannya. Mereka membaca pemikiran-pemikiran jalan revolusi, yang entah kenapa dianggap kiri dan melawan pemerintah, dan mendiskusikannya. Mereka berdiskusi tentang situasi politik Cile masa pemerintahan Salvador Allende tahun 1973 dan membandingkannya dengan situasi politik Indonesia tahun 1965. Saya tertarik ketika Naratama berkata, “Diskusi penting. Bergulat pemikiran itu wajib.”
Dibanding kawan-kawan dalam novel Laut Bercerita, yang sekali lagi saya tekankan, berasal dari kisah nyata penghilangan paksa 13 aktivis oleh rezim represif Orde Baru pada tahun 1998, saya bukanlah apa-apa. Saya tidak lebih dari manusia hedonis yang berusaha membaca buku pelan-pelan, yang sukanya bermain di mal, nongkrong di warung kopi untuk mencari wifi, lalu setelah itu bermain Mobile Legend (ML) hingga lupa berinteraksi dengan kawan-kawan di sekeliling.
Yang sering saya salahkan adalah ketua organisasi karena tidak mampu menghadirkan diskusi bagus dan menarik. Yang saya lontarkan adalah alasan-alasan untuk menutupi sekian kemalasan agar senior tidak marah pada saya seusai mendengar kondisi dan situasi yang saya laporkan, yang intinya, sekian kebobrokan yang kawan-kawan dan saya alami di organisasi bukan disebabkan oleh kinerja kami yang tak becus. Saya, mungkin juga kalian, kerap mencari kambing hitam. Menunjuk orang lain untuk menutupi kesalahan diri sendiri.
Entahlah! Ketika membaca Laut Bercerita saya merasakan betul perjuangan mahasiswa zaman dahulu. Merasakan betul pahitnya menjadi aktivis, yang memulai jejak perlawanan tanpa punya kesempatan melihat Indonesia merdeka dengan sebenar-benarnya merdeka, yang bebas mengutarakan pendapat dan ekspresi.
Saya terpekur. Hari ini, karya-karya Pramoedya Ananta Toer hanya dijadikan penghias rak buku. Nama Tan Malaka hanya disebut-sebut sebagai pemanis retorika. Saya bahkan malu saat berdiskusi ngalor-ngidul tanpa membaca buku terlebih dahulu.
*Latif Fianto, masih tinggal di bumi, menggemari nutrisasi susu dingin, setelah gagal menjadi barista kopi yang bahagia.